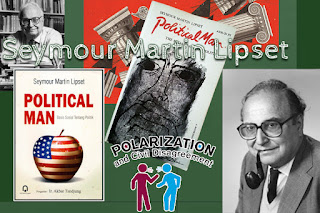Namaku Chicha Koeswoyo. Aku lahir dari orangtua yang berbeda agama. Papaku, Nomo Koeswoyo, beragama Islam dan masih keturunan Sunan Drajat, salah seorang Wali Songo. Seorang wali yang sangat terkenal sebagai penyebar agama Islam di wilayah Jawa Timur.
Mamaku seorang perempuan Kristen yang taat. Beliau masih berdarah Belanda. Dan banyak saudara-saudara dari pihak Mama yang menjadi pendeta. Walaupun berbeda agama, Papa dan Mama tidak pernah mempunyai masalah. Keduanya hidup berbahagia dan saling menghargai kepercayaan masing-masing.
Sejak kecil aku dididik secara Kristen. Seperti anak-anak Kristen lainnya, aku diikutsertakan di sekolah Minggu. Setiap kali pergi untuk melaksanakan kebaktian, Papaku sering mengantarkan kami ke gereja. Intinya, kami adalah keluarga yang sangat berbahagia. Baik hari Natal ataupun Hari Lebaran, rumah kami selalu meriah. Semua bersuka-cita merayakan kedua hari besar tersebut.
Usiaku sudah menginjak 16 tahun dan duduk di bangku kelas 1, SMA Tarakanita. Rumah tempat tinggal kami sangat berdekatan dengan masjid. Terus terang, aku sangat terganggu dengan suara azan, apalagi di saat Maghrib. Suara azan dari “toa” masjid begitu keras dan sangat memekakkan telinga. Belum lagi suara azan dari televisi. Setiap kali azan Maghrib berkumandang, aku matikan televisi karena di semua chanel, di semua stasiun tv menayangkan azan yang sama.
Di suatu Maghrib terjadilah sebuah peristiwa yang tidak disangka-sangka. Ketika itu azan Maghrib muncul di layar TV. Seperti biasa aku mencari remote control untuk mematikan televisi. Namun hari itu aku tidak bisa menemukannya. Dengan hati kesal kutelusuri sela-sela sofa, kuangkat semua bantal, kuperiksa kolong meja tapi alat pengontrol jarak jauh itu tidak juga terlihat. Karena putus asa, aku terduduk di sofa lalu duduk menatap layar TV yang sedang menayangkan azan dengan teks terjemahannya. Lalu apa yang terjadi?
Sekonyong-konyong hatiku menjadi teduh. Baris demi baris terjemahan azan tersebut terus kubaca dan entah karena apa, hati ini semakin sejuk. Aku seperti orang terhipnotis dan tubuh ini terasa sangat ringan dengan perasaan yang semakin lama semakin nyaman. Di dalam benak ini seakan-akan ada suara yang berkata padaku; “Sampai kapan kau mau mendengar panggilan-Ku, Chicha. Sudah berapa tahun Aku memanggilmu, masihkah kau akan terus berpaling dari-Ku?”
Lalu aku menangis. Entah karena sedih, marah, bingung, galau, hampa, takut atau mungkin juga semua perasaan itu ada dan berbaur menjadi satu. Aku terus menangis tanpa tahu harus melakukan apa.
Esok harinya, aku curhat pada adikku. Kami berdua memang sangat dekat satu sama lain. Adikku ini ternyata sangat berempati atas apa yang menimpaku. Dia tidak mengeluarkan satupun kata yang menyalahkan kakaknya bahkan dia berkata; “Aku akan support apapun kalau itu memang membahagiakan Kakak.”
“Terima kasih, Dik. Sekarang ikut, Kakak, yuk?”
“Ikut ke mana?” tanyanya.
Dengan diam-diam kami berdua pergi ke sebuah toko Muslim yang letaknya tidak jauh dari rumah. Di sana kami membeli mukena, Kitab Suci Al-Qurȃn dengan tafsir dan terjemahannya. Tidak lupa sebuah buku yang berjudul ‘Tuntunan Shalat’.
Sesampainya di rumah, kami berdua mempelajari cara berwudlu, melakukan shalat dan menghafal bacaannya. Setelah dirasa mampu, kami berdua mencoba mendirikan shalat bersama-sama. Perbuatan kami tentu saja di luar pengetahuan kedua orangtua. Pernah suatu kali Mama mengetuk pintu dan sangat marah karena kami mengunci kamar dari dalam. Begitu mendengar teriakan Mama, secepat kilat kami membuka mukena dan menyembunyikannya di laci paling atas.
“Dengar, ya, Nduk! Kalian nggak boleh mengunci pintu kamar. Selama kalian tinggal di rumah Mama, kalian ikut peraturan Mama,” bentak ibuku dengan galak.
“Iya, Ma,” sahutku dengan suara perlahan karena tak ingin ribut dengan Mama. Apalagi kami sangat perlu menjaga kerahasiaan ini.
Waktu terus berlalu. Bulan Ramadlan pun datang. Tentu saja di bulan suci seperti ini, kami juga ingin melakukan puasa seperti Muslim lainnya. Berpuasa dari waktu Subuh sampai Maghrib sebetulnya sama sekali tidak sulit. Masalah yang lebih pelik datang setiap kali Mama mengajak makan bersama. Mama tentunya curiga karena kami berdua selalu menolak.
“Aku udah makan di sekolah tadi, Ma,” kataku dengan suara bergetar.
Mama menatap aku dengan tajam. Sepertinya dia telah mencium ada yang tak beres dengan kami berdua. Ketegangan pun terjadi. Buatku itu adalah saat yang sangat menegangkan sampai akhirnya Mama menghela napas panjang dan berkata; “Baiklah kalau begitu.”
Bulan penuh rahmat berlalu. Suara Takbir yang begitu merdu di telinga berkumandang. Idul Fithri adalah hari kemenangan, dan kami tidak mau kehilangan momen untuk shalat bersama Jemaah yang lain. Aku dan Adikku berdiskusi menyusun strategi bagaimana cara pergi ke masjid tanpa sepengetahuan orang rumah.
Esok harinya, sekitar jam 6.30 pagi, kami mengendap-endap membuka pintu depan. Setelah itu membuka pagar sampai terbuka lebar. Kami berdua mendorong mobil dalam keadaan mesin mati supaya tidak terdengar oleh orangtua kami yang masih tenggelam dalam nyenyak. Pada Satpam yang menjaga rumah, aku berpesan; “Kalau ada yang tanya, bilang kami mau latihan basket, ya, Pak?”
“Siap, Non!” kata Pak Satpam entah curiga atau tidak.
Setelah mobil dirasa cukup jauh, aku menghidupkan mobil dan meluncur langsung ke masjid terdekat. Sesampainya di sana, banyak tetangga-tetangga menatap kami dengan wajah keheranan. Mereka tentu saja bingung karena semua orang tahu bahwa aku beragama Kristen. Bahkan barisan ibu-ibu yang duduk tepat di depan kami langsung mendekatkan kepalanya dan berbisik kepada kami.
“Cha, ngapain kamu di sini? Shalat Idul Fithri itu buat kaum Muslim. Kamu kan Kristen?”
Aku cuma tersenyum dan tidak berusaha menjawab. Sementara ibu-ibu lain terus berkasak-kusuk sambil menengok bahkan ada yang menunjuk-nunjuk ke arah kami. Kami bergeming dan tidak mempedulikan sikap orang yang merasa aneh dengan kehadiran kami. Dan akhirnya shalat Idul Fithri dapat kami ikuti dengan sukses. Dengan hati berbunga-bunga kami kembali pulang. Alhamdulillah ....
Baru saja sampai di depan pagar, di depan rumah telah berdiri Papa dan Mama. Mereka membantu membuka pagar, membuka pintu mobil lalu Mama langsung melontarkan pertanyaan tanpa basi-basi.
“Dari mana kalian?” tanya Mama dengan suara keras.
“Abis latihan basket, Ma,” sahutku. Kami berdua memang telah berganti pakaian dan semua mukena dan sajadah sudah dimasukkan ke dalam tas dengan rapih.
“Kalian jangan berbohong, ya? Mama menangkap ada yang aneh dengan kalian berdua,” kata Mama lagi.
Aku menatap Mama yang nampak sangat kesal. Sementara Papa cuma cengar-cengir bahkan mengedipkan sebelah matanya pada kami.
“Kami latihan basket, Ma. Masa Mama gak percaya sama anak sendiri?” kata adikku.
Rupanya omongan Adik membuat hati Mama tersentuh juga. Seperti sebelumnya, dia menatap kami bergantian dengan tajam, menghela napas panjang lalu berkata dengan suara halus, “Hmm ... baiklah kalau begitu.”
“Yuk, kita ke atas, Ma,” kata Papa sambil menggamit tangan Mama untuk mengajaknya pergi dari situ. Sebelum masuk ke dalam rumah, Papa sempat-sempatnya menengok ke arah kami dan mengedipkan sebelah matanya sekali lagi sambil tersenyum dengan paras jahil.
Aku masih termangu-mangu di depan rumah. Kecurigaan Mama mulai menghantui perasaanku. ‘Sampai berapa lama aku bisa mempertahankan rahasia ini?’ tanyaku dalam hati.
‘Daripada Mama yang menemukan rahasia ini, bukankah beliau lebih baik mengetahui semuanya langsung dari anaknya sendiri?’
“Mama!” Aku memanggil dan mengejar Mama yag sudah berada di dalam rumah. Mama dan Papa membalikkan badan dan menunggu apa yang akan disampaikan anaknya. Kembali kediaman berulang. Sesaat aku gentar hendak menyampaikan berita ini.
“Ya, Cha? Kamu mau ngomong apa?” tanya Papa.
Keheningan kembali mendominasi. Bibirku bergetar. Semua kata dalam tenggorokan telah berkumpul dan berdesak-desakan untuk keluar dari bibir. Aku masih diselimuti kebimbangan. Ngomong, jangan, ngomong, jangan, ngomong, jangan ....
“Chicha masuk Islam, Ma. Chicha masuk Islam, Papa. Chicha minta maaf, tapi Chicha mendapat hidayah dan tidak bisa menolak panggilan itu ....” Akhirnya tanpa dikendalikan oleh otak semua kata terlontar begitu saja.
“Alhamdulillah ...!” Di luar dugaan, Papa berteriak kegirangan mendengar berita tersebut. Tidak cukup melampiaskan kegembiraannya dengan cara itu, beliau langsung berlutut di lantai dan melakukan sujud syukur atas hidayah yang didapat anaknya.
Melihat sikap Papa, aku tentu saja menjadi lebih tabah. Dengan penuh harap, aku memandang Mama, berharap mendapat dukungan yang sama.
Mama menatapku dengan pandangan tidak percaya. Matanya melotot, dadanya kembang kempis dan bibirnya bergetar hebat.
“Hueeeeek ...!!!” Tanpa diduga tiba-tiba Mama muntah darah dan tubuhnya sempoyongan, untungnya Papa dengan sigap menangkap tubuh Mama dan mendudukkannya di sofa.
“Mamaaaaaa ...!!!” Aku menangis sejadi-jadinya. Bagaimana tidak sedih? Tidak ada kesedihan yang paling menyakitkan kecuali mengetahui bahwa kita telah menyakiti hati ibu kita sendiri.
Papa mengurus Mama dengan telaten. Perlahan-lahan kesehatan Mama berangsur-angsur membaik. Tapi sejak peristiwa itu, Mama tidak mau lagi berbicara denganku. Selama ini, Mama dan aku hubungannya sangat dekat. Melihat Mama bersikap seperti itu, aku sedih sekali.
Berkali-kali aku mengajak Mama berbicara tapi beliau tidak menyahut sehingga aku memutuskan untuk mengalah dan membiarkannya sendiri. Itu adalah salah satu periode hidup yang paling menyiksa buatku. Tapi mau bagaimana lagi? Aku hanya bisa pasrah dan menunggu perubahan sikap Mama.
Bulan demi bulan berlalu. kami masih belum berkomunikasi satu sama lain. Mama sering meninggalkan rumah. Entah kemana. Aku nggak berani bertanya, takut malahan membuatnya lebih marah. Sudah 3 bulan aku tidak berbicara dengan Mama. Hari-hari yang kuhadapi sering aku isi dengan mengurung diri di kamar sambil membaca sejarah para Nabi. Terutama kisah-kisah Rasullulah yang membuatku semakin mantap menjadi seorang Muslim.
“Braaaakkk ...!!!” Tiba-tiba pintu kamar dibuka dengan suara keras. Aku menengok dan terlihat Mama masuk dengan membawa sebuah kotak yang cukup besar. Wajahnya dingin dan sulit ditebak apa yang ada di dalam pikirannya.
“Nduk, Mama mau tanya. Kamu harus menjawab dengan tegas!” katanya.
“Iya, Ma,” sahutku dengan suara hampir tak terdengar. Dalam hati aku bersorak karena akhirnya Mama mau berbicara lagi.
“Kamu sudah mantap mau masuk Islam?” tanyanya lagi tanpa basa-basi.
“Mantap, Ma. Chicha rasa ini benar-benar panggilan Allah,” jawabku pelan tapi tegas.
“Okay, kalau begitu,” kata Mama lalu dia mengangsurkan kotak yang dibawanya ke tanganku.
Dengan terheran-heran, aku menerima kotak tersebut; “Apa ini, Ma?”
“Nggak usah banyak tanya. Kamu buka saja kotak itu sekarang juga.”
Dengan gerak perlahan, aku membuka kotak tersebut. Masya Allah! Ternyata isinya adalah Kitab Suci Al-Qurȃn, mukena, kerudung, buku-buku agama Islam yang lumayan tebalnya. Aku menatap Mama dengan pandangan bertanya.
Mama membalas menatapku dengan tajam; “Kalau kamu ingin menjadi Islam, be a good one!”
Mendengar perkatannya, aku menangis dan menghambur ke pelukan Mama. Mama memeluk aku seerat yang dia bisa. Tangisku makin menjadi-jadi dan membasahi baju Mama di bagian dada.
Setelah tangis mereda, Mama bertanya lagi; “Kamu sudah resmi masuk islam?”
“Chicha udah ngucapin dua Kalimat Syahadat, Ma.”
“Disaksikan oleh ustadz atau kyai?”
“Nggak sih, Ma. Chicha ngucapin sendiri aja.”
“Berarti kamu belum resmi masuk Islam. Besok Mama akan antar kamu ke Mesjid Al-Azhar di Jalan Sisingamangaraja. Mama udah bikin janji dengan kyai di sana untuk mengislamkan kamu.”
“Huhuhuhuhuhu ...” Aku nggak sanggup untuk mengatakan apa-apa kecuali memeluk Mama lagi sembari menangis menggerung-gerung.
Setelah perlakuan Mama yang mendiamkan aku selama tiga bulan, siapa sangka Mama akan bersikap begini akhirnya. Mamaku memang luar biasa.
Esok harinya, di Masjid Al-Azhar, aku resmi memeluk agama Islam di usia 16 tahun. Ah, bahagianya sulit dilukiskan ....
Setelah ritual mengucapkan dua Kalimat Syahadat berakhir, aku menarik Mama untuk menuju ke mobil dan kembali pulang ke rumah.
“Eh, tunggu dulu, Nduk. Sekarang kamu harus ikut Mama ke belakang.”
“Ke belakang mana, Ma?” tanyaku keheranan.
“Ke SMA Al-Azhar. Kamu harus pindah sekolah ke sana.”
“Loh? Kenapa harus pindah? Chicha udah betah sekolah di Tarakanita. Semua teman-teman Chicha ada di sana. Chicha nggak mau pindah.”
“Nduk! Denger kata Mama. Kalau kamu serius pindah ke Islam, kamu nggak boleh setengah-setengah.”
“Maksudnya gimana, Ma?”
“Tarakanita itu sekolah Kristen. Kalau kamu pindah Islam maka kamu harus bersekolah di sekolah Islam. Sekali lagi Mama bilang, kamu nggak boleh setengah-setengah. Ini peristiwa besar dan pilihan hidup kamu. Mama mau kamu total dalam menyikapi pilihan kamu sendiri.”
Lagi-lagi sikap Mama membuatku kagum bukan main. Sepertinya dia telah mempersiapkan semuanya dengan baik dan terencana.
“Mama kok bisa-bisanya punya pemikiran seperti ini?” tanyaku penasaran.
Mama menghela napas panjang lagi, lalu berucap; “Sejak kamu mengatakan mau masuk Islam, Mama sering berkonsultasi dengan teman Mama yang Muslim. Mama minta pendapat dia dan dia banyak menasihati Mama soal ini.”
“Oh, pantes Mama sering pergi belakangan ini. Biasanya kan Mama selalu di rumah.”
“Iya, Cha. Mama butuh support dan teman Mama itu sangat membantu sehingga membuat Mama jadi jauh lebih tenang.”
“Kalau boleh tahu, teman Mama siapa namanya?” tanyaku lagi.
“Namanya doktor Zakiah Darajat.”
“Itu temen Mama? Wah dia orang hebat di kalangan Islam, Ma.”
“Betul. Nama belakangnya mirip dengan Sunan Drajat, leluhur Papa kamu. Jadi setelah kamu resmi masuk Islam, rasanya kamu juga perlu berziarah ke makam beliau.”
Sekali lagi aku memeluk Mamaku. Jadi selama tiga bulan ini, dia mendiamkan anaknya bukan karena hendak mengacuhkan tapi beliau tidak tahu harus bersikap bagaimana. Beliau hendak mencari penerangan pada apa yang terjadi pada anaknya. Sudah pastilah Mama kebingungan tapi akhirnya setelah mendapat pencerahan dari doktor Zakiah Darajat, Mama sekarang malah mendukung pilihan anaknya. Pilihan anak yang berbeda dengan keyakinannya.
Ah, Mamaku memang luar biasa ....
Dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya aku hendak mengajak Mama untuk turut memeluk agama Islam. Tapi aku mengurungkan niat itu. Apa yang terjadi padaku pastilah sudah berat buat Mama. Bagaimana mungkin aku mampu mempengaruhinya sementara saudara-saudaranya banyak yang menjadi pendeta.
Beban Mama sudah sangat berat. Semua butuh waktu. Kalau memang Allah SWT mengizinkan, apa yang bagi pikiran manusia tidak mungkin pastinya akan terjadi jika Allah berkehendak.
Waktu berjalan tanpa pernah berhenti. Dengan hati tenteram, aku menjalani hidup sebagai perempuan Muslimah.
Tahun 2002, Mama meninggal dunia. Tiga bulan sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, beliau juga menjadi mualaf dan memeluk agama Islam.
Alhamdulillah ...! Terima kasih, ya, Allah ...!
Ah, Mamaku memang luar biasa ...!
Persembahan buat semua perempuan hebat di Indonesia ...!
Dikisahkan oleh:
Chicha Koeswoyo
Sumber: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10156390517326107&id=684961106